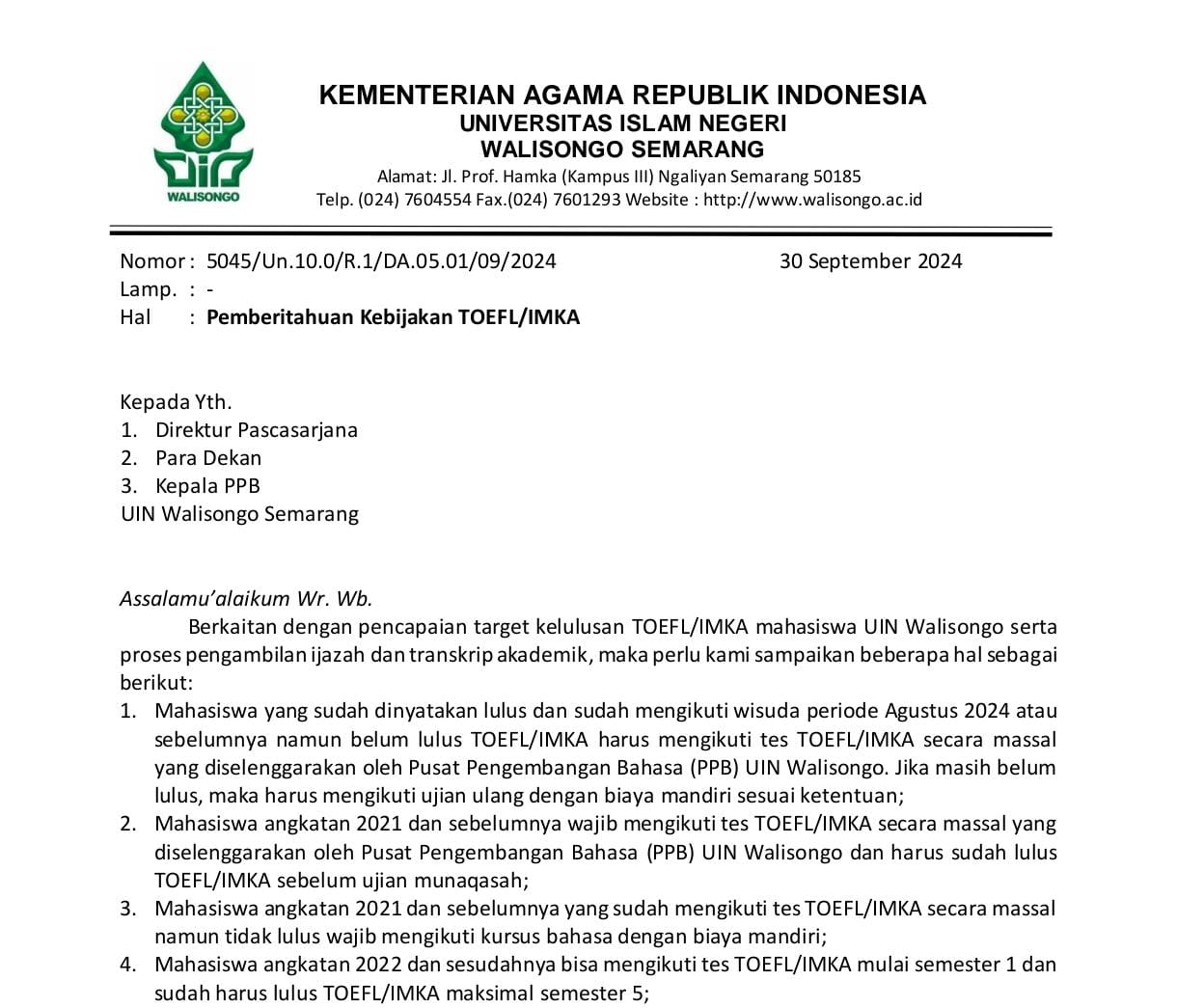Berita
Cadar dan Bayang-bayang Radikalisme
Benarkah cadar identik dengan radikalisme? Tepatkah kampus menerbitkan aturan yang melarang mahasiswi bercadar dengan alasan melawan radikalisme?
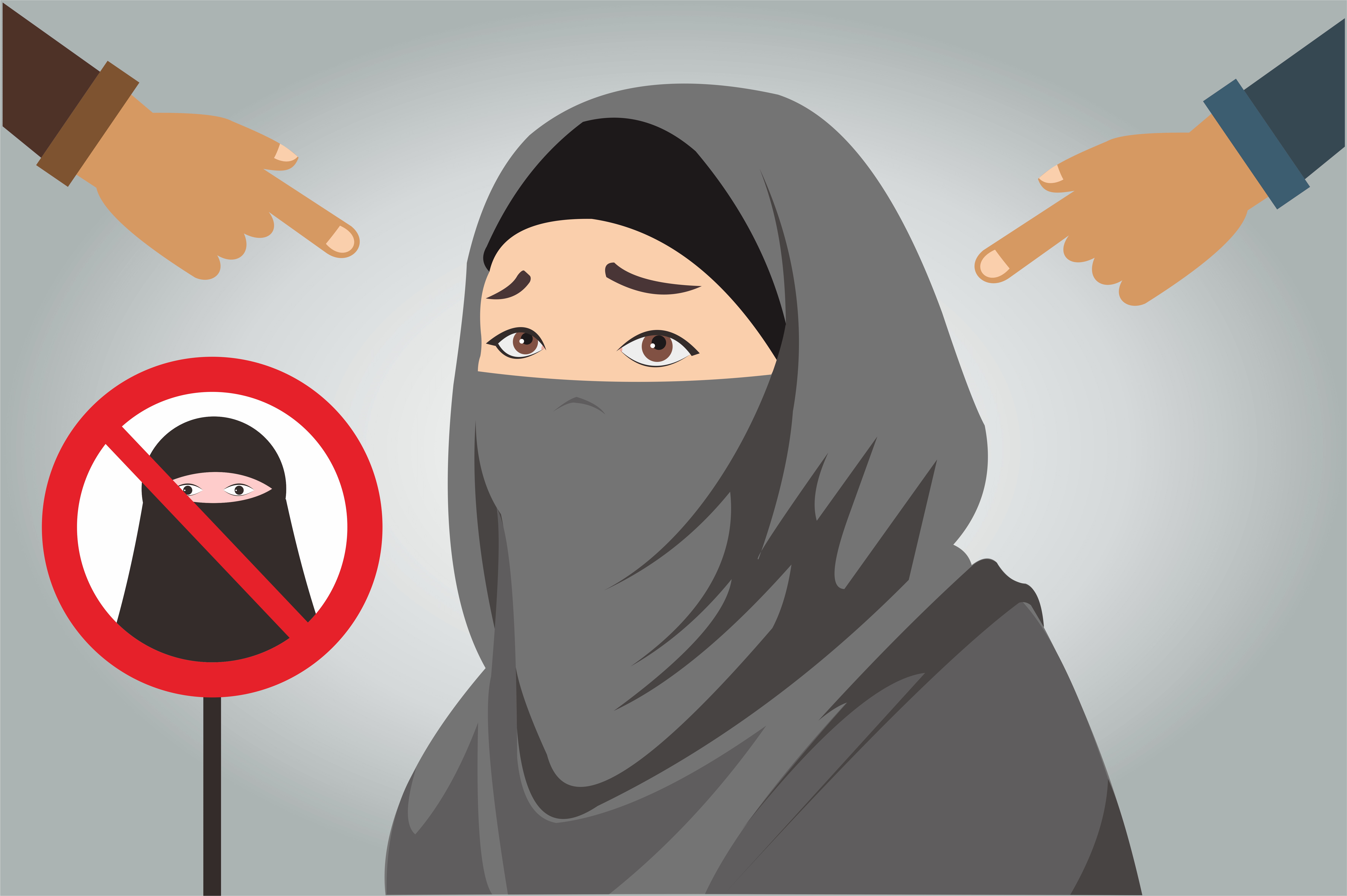

Benarkah cadar identik dengan radikalisme? Tepatkah kampus menerbitkan aturan yang melarang mahasiswi bercadar dengan alasan melawan radikalisme?
Aturan pelarangan penggunaan cadar di UIN Walisongo Semarang masih menjadi perdebatan. Pasalnya, menurut SK Rektor Nomor 19 Tahun 2005 pasal 9 tentang tata cara berpakaian, terdapat beberapa larangan untuk mahasiswi seperti tidak boleh bercadar, memakai kaos, dan celana jeans ketat selama mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor, dan kegiatan akademik lainnya. Selain itu mahasiswi juga dilarang memakai pakaian ketat, tembus pandang, baju pendek, serta berdandan berlebihan diluar kepatutan.
Sejak tahun 2016, SK Rektor Nomor 19 Tahun 2005 pasal 9 sudah digantikan dengan SK Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang tata cara berpakaian. Secara umum, isi SK tersebut masih sama dengan SK tahun 2005. Hanya saja, pelarangan penggunaan cadar sudah dicoret dari ketentuan berpakaian. Namun hingga saat ini, pelarangan tersebut masih digaungkan dengan kuat.
Seperti polemik pada tahun 2018, Wakil Rektor III UIN Walisongo kala itu, Suparman Syukur, mengatakan bahwa bercadar dianggap berlebihan. Hal tersebut diperkuat oleh Rektor UIN Walisongo periode 2018 Muhibbin, menurutnya sah-sah saja bagi UIN Walisongo menerapkan aturan tersebut.
Adanya peraturan tersebut, membuat salah seorang mahasiswi yang bercadar (AF) merasa keberatan. Menurutnya peraturan tersebut harus dicabut, karena cadar tidak bisa menjadi acuan baik buruknya seorang mahasiswa. Menurut AF, tidak sebaiknya kampus menggunakan dalih bahwa cadar kerap disandingkan dengan pemahaman radikal.
“Kalau kampus berdalih radikal atau mungkin cara berpakaian yang menutup aurat itu sudah cukup, maka seyogyanya yang pakai cadar juga jangan dilarang. Kan mereka sudah menutup aurat,” tuturnya pada kru LPM MISSI, Minggu (5/4).
AF memilih bercadar bukan tanpa alasan, ia ingin meneladani akhlak Sayyidah Fatimah yang disebut sebagai pemimpin para wanita di surga. Ia juga berpendapat bahwa pakaian trend zaman sekarang, nantinya tidak akan dibawa ke surga. AF meyakini, semakin berpakaian tertutup, seorang perempuan dianggap semakin berakhlak.
Antara Stigma dan Tengara
Stigmatisasi terhadap mahasiswi bercadar telah menjadi hal yang melekat di lingkungan sekitar. Pasalnya, tidak semua orang dapat menerima perbedaan dengan lapang. Seperti yang terjadi kepada AF ketika pembelajaran tatap muka masih berlangsung. AF menceritakan bagaimana dirinya mendapat stigma dari beberapa dosen ketika memakai cadar. Karena ia sadar bahwa dirinya masih berada di bawah naungan instansi, AF memilih untuk menyesuaikan keadaan ketika memakai cadar.
“Kalau sekiranya dosen tidak menghargai, berstigma negatif dan menilai buruk pada saya, biasanya saya mengganti cadar dengan memakai masker. Namun ketika berhadapan dengan dosen yang baik-baik saja, saya tetap memakai cadar,” tandasnya.
AF bukan satu-satunya mahasiswi yang merasakan dampak pelarangan bercadar di kampus. Pengalaman serupa dialami oleh (NA), mahasiswi bercadar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang sangat menyayangkan adanya peraturan tersebut. Menurutnya, peraturan pelarangan penggunaan cadar sangat konyol jika masih diterapkan.
“Pemakaian cadar merupakan kebebasan berekspresi seseorang. Jika kampus menerapkan peraturan tersebut, maka termasuk merampas hak seseorang dalam berpakaian,” kata NA kepada kru LPM Missi.
NA juga bercerita, bahwa dirinya sudah bercadar sejak di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan sebelum masuk UIN Walisongo, ia tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Sehingga, mau tidak mau ia harus menjaga niat yang sudah dimulai sejak dulu.
“Teman-teman saya mendukung jika saya menggunakan cadar. Namun, selama menggunakan cadar di luar kampus untuk berkegiatan sosial, tidak jarang masyarakat memandang saya dengan tatapan sinis, bahkan sampai menjadi sorotan publik,” tambahnya.
Di samping itu, NA juga mengaku bahwa hal-hal seputar stigma hingga diskriminasi telah menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Bahkan, lanjut NA, salah satu dosen UIN Walisongo pernah menerbitkan buku yang menyinggung cadar. Katanya, buku tersebut sangat menyudutkan orang bercadar dan disangkutkan dengan radikalisme.
“Membaca judulnya saja sudah membuat saya geram dan sakit hati. Padahal negara kita mayoritas muslim, namun orang-orang di dalamnya justru yang menciptakan islamophobia,” jelasnya.
Dianggap Sudah Toleran
Peraturan pelarangan penggunaan cadar yang digaungkan di UIN Walisongo bukanlah hal baru. Menurut data tahun 2018, tercatat ada sekitar 14 mahasiswi UIN Walisongo yang menggunakan cadar. Meskipun begitu ada juga mahasiswa yang menganggap peraturan ini harus ditegakkan.
“Pelarangan peraturan ini ya sah-sah saja, soalnya itu peraturan dari kampus. Kalaupun tidak mau menuruti, ya berarti silahkan cari kampus yang memperbolehkan menggunakan cadar,” ujar Sapri, Sapri Aziz, mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Senin (6/4).
Sapri berpendapat bahwa peraturan ini bukanlah bentuk diskriminasi maupun perampasan hak kebebasan berekspresi. Dirinya juga menganggap bahwa ini merupakan tindakan yang cukup adil untuk ditetapkan. Mengingat bahwa dalam belajar tatap muka, susah untuk mengenali seseorang jika memakai cadar.
Hal senada dikatakan oleh mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Efi Nur Jannah. Menurutnya, selain harus saling kenal ketika belajar tatap muka, seorang muslim juga tidak harus bercadar jika ingin menutup aurat.
“Cara maksimal untuk melindungi diri tidak harus memakai cadar. Wajah bukan termasuk aurat, jadi tidak wajib bagi seorang muslim menggunakan cadar,” tutur Efi, Senin (6/4).
Efi mengaku bahwa dirinya juga menggunakan cadar ketika berpergian jauh. Namun untuk kegiatan sehari-hari, ia menghindari menggunakan cadar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Aku memilih pakai cadar karena lebih nyaman. Tapi aku tetap tidak setuju kalau cadar itu dianggap sebagai budaya,” jelasnya.
Adab dan Ilmu
Jilbab di UIN Walisongo layaknya barang wajib yang digunakan ketika berada di lingkungan kampus. Tidak bisa dipungkiri, beberapa mahasiswi UIN Walisongo memilih untuk tidak menggunakan jilbab dalam kegiatan sehari-hari. Selain belum nyaman, jilbab kiranya hanya dianggap sebagai simbol. Hal tersebut diungkapkan oleh mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), AR.
“Saya memang sering tidak memakai jilbab jika bepergian. Tapi, karena saya kuliah di UIN ya mau tidak mau harus mematuhi peraturan. Hanya sebatas itu. Bisa dikatakan saya memakai jilbab bukan datang dari hati,” ucapnya, Kamis (15/4).
Menurut pengakuannya, AR juga sering mendapat teguran dan kritikan dari teman-teman bahkan orang tuanya. Namun hal tersebut tidak membuat AR goyah dengan pilihannya. Menurutnya, pakaian tidak menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Dengan alasan, setiap manusia juga berhak memilih kebebasan.
“Mengapa orang sibuk berkomentar, padahal diri saya sendiri yang melakukan? Toh, seorang yang berilmu tidak dicerminkan dari apa yang mereka kenakan. Dia mau pakai cadar bahkan tidak pakai jilbab sekalipun, tidak bisa mencerminkan kemampuan belajar mereka,” ungkap AR.
Sementara itu mahasiswi KPI semester 8, DN juga mengungkapkan bahwa jilbab yang ia kenakan memang wajib adanya. Namun ada kalanya jilbab tidak dipermasalahkan dalam hal-hal yang menyangkut privasi seseorang.
“Apapun yang digunakan seseorang dalam berpakaian, kita tidak berhak mengatur apalagi memaksa. Karena dosa ataupun pahala itu kan diri kita masing-masing yang menerima,” jelasnya.
DN menambahkan, bahwasannya tidak ada hubungannya antara pakaian dengan tinggi rendahnya ilmu seseorang. Hanya saja, masyarakat sering mengaggap bahwa orang yang berpakaian syari, berjilbab adalah orang yang berilmu tinggi, begitu pula sebaliknya.
“Mungkin orang-orang lebih gampang menilai dari apa yang terlihat seperti wajah, penampilan, dan pakaian misalnya. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya hal-hal apa yang mendasari kita memilih berekspresi seperti itu,” tegasnya.
Cadar dari Perspektif Lain
Melihat berbagai sudut pandang peraturan pelarangan cadar di UIN Walisongo kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN Walisongo, Luthfi Rahman. Ia mengatakan bahwa peraturan tersebut memang sudah lama diterapkan. Dengan alasan, sebagai langkah simpatik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pertimbangan pelarangan mahasiswi pakai cadar itu adalah pertimbangan yang sifatnya antisipatif. Biasanya, orang bercadar itu diidentikkan sebagai orang yang radikal. Maka peraturan ini sebagai antisipatif masuknya gerakan radikal di UIN,” jelas Luthfi pada Kru MISSI, Senin (6/4).
Luthfi juga bercerita mengenai aktivitas orang bercadar yang terhubung dalam gerakan radikal. Contohnya seperti peristiwa pengeboman Gereja Katredal di Makassar pada 28 Maret lalu. Tidak lain pelaku dari peristiwa tersebut adalah seorang perempuan bercadar. Stigma tersebut seolah merekonstruksi masyarakat dalam memandang seorang yang bercadar.
Luthfi menambahkan, bahwa memang tidak semua orang bercadar adalah radikal. Namun, ada baiknya jika langkah antisipatif tersebut lebih awal ditegakkan.
“Semua kerangka yang terhubung dalam konteks ini harus dipahami, mereka yang berafiliasi dalam golongan fundamentalis. Ini harus dipahami bukan hanya dari Hak Asasi Manusia (HAM), tapi kembali juga ke langkah antisipatif,” lanjut Luthfi.
Sedangkan seorang penulis opini serta aktivis muda Gusdurian, Kalis Mardiasih, berpendapat bahwa stigma cadar atau jenggot yang dikaitkan dengan ekstremis teroris juga tidak tepat-tepat amat. Melalui tulisannya yang berjudul Menyambut Generasi Cadar Garis Lucu, Kalis menceritakan seorang bercadar yang ternyata tidak kaku dalam pemikiran maupun perlakuannya. Tulisan tersebut menarik kesimpulan bahwa jilbab atau cadar adalah cara berpakaian saja. Selebihnya, perempuan bercadar tidaklah benar kalau langsung diidentikkan dengan terorisme.
Padahal Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, seperti dikutip pada tirto.id tahun 2018 mengatakan bahwa, pelarangan penggunaan cadar yang ditetapkan di sejumlah universitas bukanlah kebijakan yang tepat. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam diskriminasi. Jika peraturan tersebut ditetapkan dengan alasan mengantisipasi gerakan radikal, itu bukan alasan yang tepat.
Pembatasan Kebebasan Berekspresi?
Penggunaan cadar di lingkungan sosial memang kerap menjadi sorotan. Namun perlu diingat bahwa publik juga memiliki hak untuk mendapat keamanan. Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Awigra mengatakan bahwa kebebasan berekspresi bisa dibatasi dengan ketentuan hukum dan tujuan perlindungan, keselamatan dan kesehatan publik, hingga ketertiban umum.
“Eskpresi pemakaian cadar memang bisa dibatasi dengan hal-hal tertentu. Tujuannya, untuk mengetahui identitas siapa di balik cadar, khususnya saat dibutuhkan untuk urusan keamanan,” ucap Awigra, Jumat (30/4).
Selain dalam lingkup publik, Awigra menambahkan, penggunaan cadar di ranah pendidikan juga harus diperhatikan. Walapun bercadar merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi, tak bisa dipungkiri jika lembaga pendidikan mempunyai aturan yang menunjang tujuan pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari sisi nilai dan moralitas di lapangan.
“Yang menjadi sorotan bukan soal salah atau benar, tapi soal etis dan nilai yang sering menjadi pertanyaan,” kata Awigra.
Bagi lembaga pendidikan yang membatasi ataupun melarang penggunaan cadar, Awigra berpendapat bahwa seharusnya ada alasan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
“Pembatasan tersebut harus diputuskan dengan sangat hati-hati, karena menyangkut pengurangan hak. Tetapi, akan lebih baik lagi jika lembaga menyertakan alasan secara gamblang, misal ketika makan bersama, ataupun masuk pada pelajaran tertentu,” pungkasnya.
Hingga tulisan ini diterbitkan pihak kampus melalui Rektor, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III tidak merespon dan memberikan pernyataan kepada kru LPM MISSI mengenai polemik penggunaan cadar di UIN Walisongo.
Sebagai mahasiswi yang menggunakan cadar, AF dan NA berharap agar pihak kampus dapat menimbang kembali peraturan pelarangan penggunaan cadar. Karena bagaimanapun, setiap orang berhak mengekspresikan kebebasan.
“Sebaik-baiknya peraturan, seharusnya tidak merugikan pihak yang merasa terkucilkan. Sekalipun peraturan tersebut terlihat sepele, keadilan harus tetap ditegakkan,” harap AF.
Penulis: Sabrina Mutiara F.
Tulisan ini bagian dari program Workshop dan Story Grant Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.