esai
Bukan Salah RKUHP Demokrasi Mati
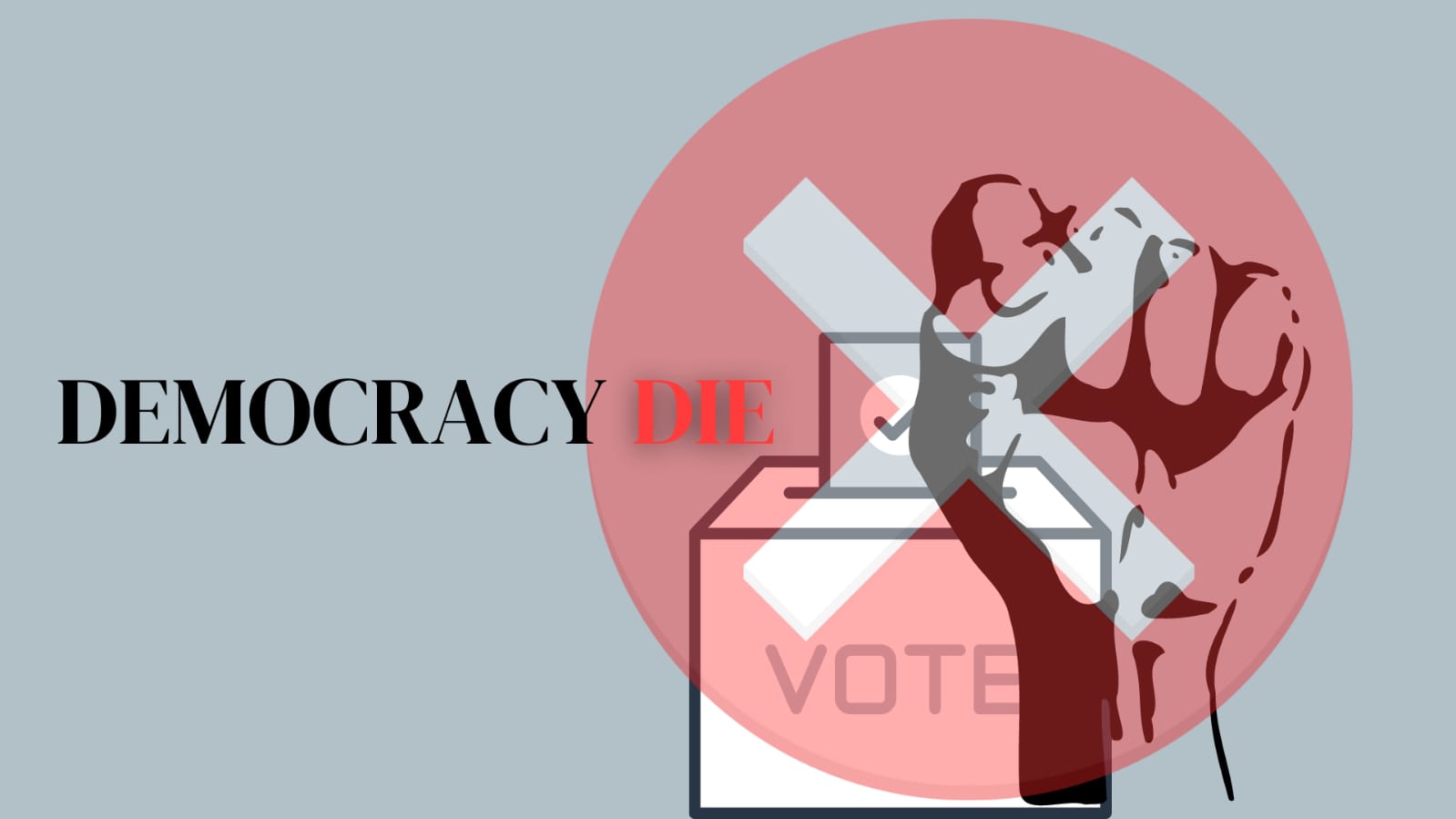
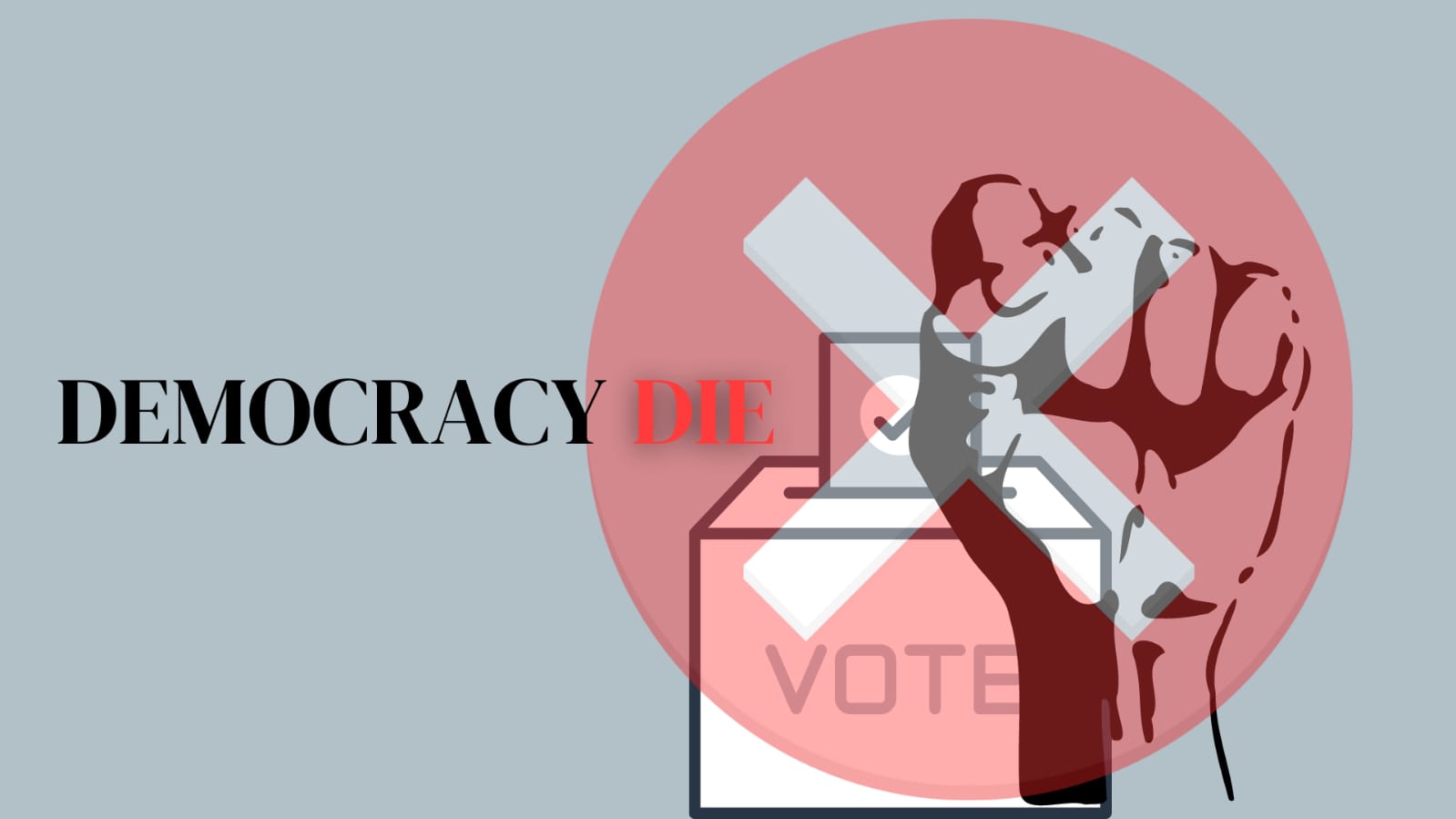
Tidak barang sebentar hasrat untuk menulis perihal potensi matinya demokrasi di Indonesia ini tumbuh. Keinginan tersebut berangkat dari diskursus yang digelar baru-baru ini, yaitu terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap sebagai pasal karet yang bermasalah, dan tidak merepresentasikan hak-hak rakyat.
Giat demonstrasi pun mulai tampak dilakukan kembali di beberapa daerah sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah selaku penyelenggara negara. Dengan premis singkat ini, bisakah hal tersebut dijadikan sebagai indikator kematian demokrasi?
Mari kita ingat bahwa tiga tahun silam, RKUHP sempat ditunda pengesahannya tepatnya di tahun 2019. Kini wacana pengesahannya kembali bergulir dengan cepat. Tetapi di satu sisi, belum ada iktikad dari DPR untuk menerbitkan draft RKUHP yang baru. Seolah-olah penolakan keras dari berbagai elemen sebelumnya menyangkut kecacatan RKUHP dengan pasal-pasalnya yang mengancam kebebasan berpendapat dan berpotensi merusak demokrasi tak ada gunanya. Dengan demikian, apakah demokrasi di Indonesia memang sudah mati sejak saat itu?
Tulisan ini tidak ditulis untuk mengabarkan kematian demokrasi, apalagi memperingati kematiannya. Toh, tak pernah ada tanggal atau catatan kematiannya. Tapi yang menarik kemudian adalah siapakah yang berpotensi sebagai pembunuh sentral dari demokrasi itu sendiri?
Agaknya terlalu lancang ketika membawa kata presiden atau DPR di sini. Mereka dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Mereka merupakan produk dari demokrasi sendiri, apakah mungkin yang diberi mandat justru malah membunuh tuannya sendiri?
How Democracies Die?
Sebenarnya, indikator kematian demokrasi tak melulu dimulai dengan ketidakbecusan wakil rakyat atau tulinya kepala negara terhadap rakyatnya. Mari kita ingat kembali postingan nyentrik Anies Baswedan yang sedang duduk santai di kursi sambil membaca buku How Democracies Die yang ditulis oleh profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.
Patut untuk diketahui bahwa kita tidak sedang membicarakan sosok itu sebagai capres di tahun 2024. Sekaligus menegaskan bahwa makna dari demokrasi tidak hanya soal taatnya pejabat negara terhadap konstitusi serta panggung politik yang tentu disertai dengan atmosfer panasnya hubungan antar masyarakat.
Hal menarik dari buku yang dibaca oleh gubernur DKI Jakarta itu ialah dua profesor ilmu pemerintahan selaku penulisnya tadi tak berbicara soal kematian demokrasi secara praktis semata. Melainkan telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk mengetahui bagaimana demokrasi menjadi kuat dan apa yang membuatnya menjadi hancur.
Menurut mereka, setidaknya ada empat hal yang menyebabkaan demokrasi mati. Dimulai dari penolakan (komitmen yang lemah terhadap) aturan main yang demokratis, penolakan legitimasi lawan politik, toleransi atau dorongan kekerasan dan yang terakhir kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.
Dari keempat hal diatas yang menarik adalah poin pertama. Bisa kita lihat bagaimana pemerintah kita saat ini sedang abai dan menyepelekan aturan main demokrasi. Pengabaian pada produk hukum itu bisa kita lihat dari proses pembahasan hingga rencana pengesahan RKUHP.
Ada banyak prosedur pembuatan undang-undang yang diabaikan termasuk tergesa-gesanya dalam hal pengesahan sementara masih banyak pasal-pasal yang kontroversial. Proses prematur demikian bisa menjadikannya sebagai produk hukum yang cacat formil.
Lebih lanjut, jika ditemui dugaan terjadinya pelanggaran formil dalam pembentukan legitimasi UU, maka jalan selanjutnya yang dapat ditempuh dengan menggugatnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji kelayakannya. Namun, penyerahan keputusan kepada MK itu tak selamannya baik. Sebab dalam perkembangannya, hal ini membuat DPR sebagai pembuat UU selalu berkilah dengan menyarankan melakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi.
Benarkah Demokrasi Telah Mati?
Fenomena di atas membuat kita menyadari betapa rendahnya literasi moral terhadap demokrasi di Indonesia. Ketika lembaga legislatif yang mewakili rakyat memiliki tanggung jawab untuk membuat undang-undang justru setelah jadi malah menyerahkannya pada konstitusi untuk diuji. MK sendiri juga memiliki fungsi mengawasi legislatif, sehingga jika ada sebuah gugatan perihal rancanagn UU yang cacat formil. Maka MK harus mengabulkan permohonan untuk pengujian RUU tersebut.
Tapi bagaimana bila DPR RI sendiri yang menyerahkan sepenuhnya rancangan UU kepada MK untuk diuji? Maka Perkara ini bukan lagi kecacatan formil undang-undang, tapi juga kecacatan logika DPR. Jika hal ini terus berlangsung, lembaga peradilan ini tak ubahnya menjadi septictank dari pekerjaan bermasalah yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR.
Sama halnya, jika RKUHP yang mengancam kebebasan berpendapat dan melanggengkan penguasa di singgsana kekuasaan disahkan. Mestilah rakyat bukan lagi tuan yang memberi mandat setiap pemilu dilaksanakan. Tapi layaknya UU yang dibuat untuk memuluskan akal bulus penguasa, rakyat tak ubahnya adalah sebuah kakus, tempat pemerintah membuang tahi-tahi kotornya.
Jauh-jauh hari sebelum adanya penolakan terhadap RKUHP, atau adanya penolakan secara tegas oleh berbagai pihak, dimana ditemukan 14 pasal bermasalah dalam rancangan UU tersebut, bukanlah kali pertama terjadi.
Ingatkah kita ketika Indonesia diwarnai oleh demonstrasi sejak september 2020 lalu. Saat itu yang turun ke jalan bukan saja mahasiswa, tapi juga pelbagai elemen masyarakat seperti buruh pabrik, petani hingga pelajar untuk menyuarakan agar adanya delegetimasi hukum bermasalah di negeri ini. Sebut saja berbagai produk hukum bermasalah sejak pertengahan tahun 2019 seperti revisi UU KPK, UU Minerba, UU Ciptaker dan RKUHP yang sedang ramai dibahas saat ini.
Aksi yang didasari pada “Reformasi Dikorupsi” itu memang merebut banyak perhatian. Sebab aksi tidak hanya dilakukan di depan gedung DPR saja tapi juga meluas hingga ke penjuru Indonesia. Siapa serupa terjadi pada tahun 1998.
Sayangnya, gerakan massa yang banyak itu tak sepenuhnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Jangankan aspirasi diterima. Mereka malah disambut dengan tidak ramah, tindakan represif yang dilakukan aparat untuk membubarkan demonstran tidak terelakkan.
Padahal sesungguhnya yang dilukai oleh aparat bukanlah fisik mereka, ataupun yang terpecundangi bukanlah pengorbanan mereka. Melainkan yang terluka adalah hak untuk menyampaikan pendapat yang harusnya dilindungi oleh konstitusi. Setelah ini semua, apa jadinya bila RKUHP dengan pasal-pasal bermasalah dan mengancam kebebesan berpendapat itu disahkan?
Merujuk pada Tirto.id setidaknya ada 390 kasus kekerasan yang dilakukan aparat dalam aksi reformasi dikorupsi. Serta 1.489 orang yang ditangkap, dan 380 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Belum lagi tambahan deretan nama dari mereka yang meregang nyawa setelah berusaha untuk menyampaikan pendapatnya di negeri ini. Bagus Putra Mahendra, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, Randy, dan Yusuf Kardawi. Lupakah kita dengan apa yang menimpa mereka?
Menyebut bahwa demokrasi telah mati disaat sudah banyak yang dikorbankan untuk memperjuangkan suara rakyat di negeri ini barangkali juga adalah sebuah penghinaan. Tapi setelah melihat ironi yang terjadi ni negeri ini, dimana suara rakyat terdengar sumbang dan aspirasi hanyalah tinggal aspirasi.
Bukankah demokrasi di negeri kita sudah di depan jurang kematian, sudah berada di tepi kubur. Mau sebesar apapun derita yang kita peroleh dalam memperjuangkannya. Layaknya sebuah perpisahan dan kematian, yang paling berat adalah hari-hari setelahnya, ketika kemanapun kita mencari keadilan ia tak pernah ditemukan, ketika sekeras apapun rakyat menyuarakan aspirasinya pemerintah pura-pura tuli.
Penulis: Ihsanul Fikri





